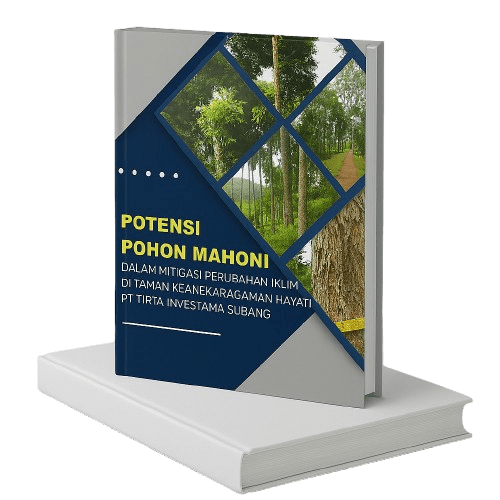Dilema PS: Kegagalan dan Keberhasilan Menjaga Relasi Kuasa Masyarakat-Negara atas Sumberdaya Hutan
Di Jawa, pada era ini mulai diperkenalkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), sebuah adaptasi dari Joint Forest Management, skema Perhutanan Sosial di India. Melalui PHBM, Perhutani menawarkan skema bagi hasil dalam pengelolaan hutan dengan porsi 25% masyarakat, dan 75% Perhutani. Sementara itu di luar Jawa, pemerintah mulai mengubah arah Hutan Kemasyarakatan dari yang semula non tenurial menjadi tenurial: masyarakat bisa terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam jangka waktu yang cukup panjang (5 tahun ketika mendapat ijin sementara, 35 tahun ketika berhasil mendapatkan ijin definitif). Meskipun demikian, pada era ini mekanisme penyelenggaraan perhutanan sosial, di Jawa maupun di luar Jawa, dipandang masih sangat kompleks, sehingga kecil kemungkinan masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang memadai dari program-program Perhutanan Sosial yang ada.
Ketiga, era penguatan (2016-sekarang), yang ditandai dengan penetapan Perhutanan Sosial sebagai bagian dari program strategis nasional. Pada era ini, arus utama perhutanan sosial tidak lagi di jawa, sebagaimana yang terjadi pada dua era sebelumnya, melainkan di luar Jawa. Pada era ini program Perhutanan Sosial bahkan mengalami kebaruan-kebaruan yang signifikan, dari mulai intervensinya dalam pengelolaan hutan di Jawa (melalui Ijin Pengelolaan Hutan Perhutan Sosial/ IPHPS), dukungan kebijakan yang sangat beragam (tidak hanya mengandalkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), target luasan yang luar biasa (12,7 juta hektar), penggabungan berbagai model Perhutanan Sosial ke dalam satu kebijakan, penyederhanaan mekanisme perijinan hingga kemudian bisa meningkatkan kecepatan layanan, penyediaan layanan permodalan dan bantuan teknis, penguatan sistem tenurial, mobilisasi kalangan masyarakat sipil, promosi yang gencar kepada publik melalui berbagai media, hingga integrasi Perhutanan Sosial ke dalam platform-platform online yang kemudian dikenal dengan PS 4.0.
Proyek will to improve
Tentu saja, sebagaimana yang sudah disinggung di muka, segenap upaya yang sudah dilakukan di tiga era Perhutanan Sosial itu tidak lantas secara otomatis bisa membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Meskipun demikian, kita juga tidak bisa mengatakan begitu saja bahwa dalam 50 tahun perjalanan, Perhutanan Sosial ternyata tidak bisa mengatasi persoalan kehutanan dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Singkatnya, kita tidak bisa melakukan generalisasi bahwa Perhutanan Sosial adalah sebuah resep ajaib untuk mengatasi persoalan kehutanan dan masyarakat desa hutan; atau sebaliknya, bahwa Perhutanan Sosial adalah racun bagi pengelolaan hutan. Pada kenyataannya, sebagaimana yang terjadi pada skema-skema yang oleh Li (2007) disebut sebagai will to improve, untuk tidak mengatakan skema pembangunan dan pengembangan tata kehidupan masyarakat, Perhutanan Sosial pun akan selalu berhadapan dengan oposisi biner: kegagalan dan keberhasilan. Melihat kasus Kalibiru dan Wanagiri, mungkin kita akan bisa mengatakan program Perhutanan Sosial berhasil. Tapi melihat Muara Merang dan Pulangpisau, mungkin kita akan mengatakan sebaliknya.
Dinamika capaian semacam itulah yang menjadi catatan dalam tulisan ini. Bagaimanapun, kalau kita menggunakan pisau analisis Li (2007), Perhutanan Sosial adalah proyek will to improve kalangan trusteeship, mereka-mereka yang berstatus sebagai “wali masyarakat”, kalangan elit dan cerdik pandai yang senantiasa memiliki kepedulian, jika bukan obsesi, untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Proyek will to improve selalu saja seperti pedang bermata dua: di satu sisi bisa menciptakan hal-hal positif, di sisi lain bisa menimbulkan hal-hal negatif. Studi Li di Sulawesi Tengah pada proyek konservasi dan relokasi kalangan masyarakat pedalaman, hal yang sama-sama memiliki motif perbaikan tata kehidupan dan dan lingkungan, pada akhirnya justru menciptakan kekacauan yang sampai saat ini tidak kunjung bisa diselesaikan (kasus pendudukan TN Dongi dongi).
Perhutanan Sosial juga mengandaikan dan menjanjikan perbaikan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Melalui program formalisasi tenur dan kelembagaan, program Perhutanan Sosial menawarkan harapan bahwa dengan kelembagaan dan tenur formal, masyarakat akan bisa melakukan investasi secara aman dalam jangka panjang di wilayah kelolanya, masyarakat juga akan bisa mengkases bantuan-bantuan teknis dan permodalan yang disediakan pemerintah, masyarakat juga akan bisa meningkatkan produktivitas lahannya, dan lain sebagainya. Asumsi yang dikembangkan adalah bahwa tanpa dukungan tenur dan kelembagaan formal yang diselenggarakan negara, model-model kehutanan masyarakat yang selama ini berkembang, seperti simpukn, repong, tembawang, parak, dan lain sebagainya, setiap saat akan bisa tergusur oleh kepentingan pembangunan dan industrialisasi. Tenur dan kelembagaan formal, dengan demikian adalah jaminan akan keberlanjutan sekaligus peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, hal yang selalu ditawarkan oleh proyek-proyek will to Improve di mana pun dan kapan pun. (Apakah memang…..)